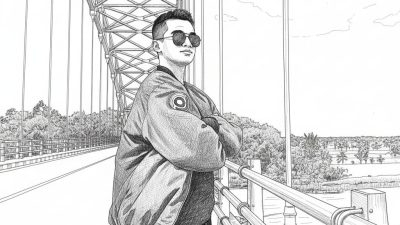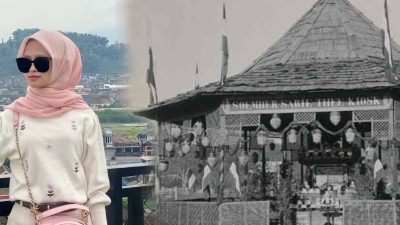Oleh : Rifky Gimnastiar
(Akademisi Fakultas Tarbiyah IAI At-Taqwa Bondowoso)
Sejarah adalah cermin yang tidak selalu jernih. Kadang ia memantulkan wajah dengan setengah cahaya, kadang dengan bayangan pekat yang menakutkan. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah salah satu cermin itu: di satu sisi ia pernah menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dengan jutaan anggota dan basis massa luas; di sisi lain ia diingat sebagai dalang dari sebuah tragedi kelam yang merenggut banyak nyawa. Menulis tentang PKI berarti menulis tentang paradoks, tentang harapan dan luka, tentang capaian politik dan darah rakyat.
Di era 1950-an hingga awal 1960-an, PKI tumbuh subur. Ia hadir bukan hanya sebagai partai politik, melainkan sebagai gerakan sosial. Petani menemukan ruang untuk bersuara lewat organisasi tani, buruh punya wadah perjuangan lewat serikat-serikat, bahkan seniman dan intelektual ikut terlibat dalam lembaga kebudayaan yang terinspirasi gagasan kiri. Di desa-desa Jawa, Bali, hingga Sumatera, PKI menjadi simbol harapan baru bagi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan.
Dalam catatan sejarah, PKI pernah mencapai suara hampir 16% dalam Pemilu 1955, menjadikannya partai terbesar keempat. Itu bukan angka kecil. Angka itu menunjukkan betapa banyak rakyat melihat PKI sebagai jawaban atas kesenjangan sosial yang mereka alami. Janji tentang keadilan, reforma agraria, dan penghapusan ketimpangan menggema di telinga mereka yang lelah hidup di bawah struktur feodal.
Tidak bisa dipungkiri, PKI memberi warna pada demokrasi Indonesia kala itu. Partai ini melahirkan organisasi-organisasi massa seperti SOBSI (buruh), BTI (tani), LEKRA (seni-budaya), dan Gerwani (perempuan). Lewat itu semua, gagasan tentang kesetaraan, pendidikan politik rakyat, dan keberanian untuk bersuara menjadi nyata. Ada dimensi positif yang jarang disentuh ketika kita membicarakan PKI: keberaniannya mengorganisir massa rakyat kecil dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya.
Namun, setiap harapan sering menyimpan benih masalah. PKI tumbuh dalam situasi Perang Dingin, ketika dunia terbelah dua kutub: kapitalisme dan komunisme. Indonesia pun terseret dalam tarikan itu. Keberpihakan PKI pada ideologi komunis global menimbulkan kecurigaan, terutama dari kalangan militer, kelompok Islam dan kekuatan politik lain yang khawatir akan dominasi partai ini.
PKI juga kerap terjebak dalam retorika konfrontatif. Konflik agraria misalnya, sering berujung pada gesekan dengan kelompok lain, termasuk Nahdlatul Ulama yang juga memiliki basis massa di desa.
Pertarungan ideologi menjadi semakin panas dan ruang kompromi makin sempit. Dari sinilah, benih tragedi mulai tumbuh: perbedaan tidak lagi dilihat sebagai kekayaan bangsa, melainkan sebagai ancaman eksistensial.
Ketegangan itu mencapai titik klimaksnya pada malam 30 September 1965. Sejarah resmi Orde Baru mempelintir PKI sebagai dalang penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI AD dan satu perwiranya. Tetapi hingga kini, siapa sebenarnya yang mengatur peristiwa itu masih menjadi misteri. Sejumlah teori muncul: keterlibatan internal PKI, perpecahan di tubuh militer, bahkan campur tangan intelijen asing. Semuanya membuka kemungkinan, tapi tidak menyuguhkan jawaban final.
Bagi saya, G30S bukan hanya soal siapa dalangnya. Ia adalah puncak emosi politik yang telah lama dibangun. Kebencian, ketakutan, dan propaganda yang menumpuk selama bertahun-tahun meledak dalam satu malam berdarah, lalu menyapu kotor jutaan nyawa selepasnya. PKI, yang tadinya menjadi rumah bagi jutaan rakyat kecil, tiba-tiba berubah menjadi simbol pengkhianatan yang harus dilenyapkan.
Ironisnya, setelah tragedi itu, yang paling banyak menjadi korban bukanlah elite PKI, melainkan rakyat biasa. Mereka yang hanya menjadi anggota organisasi tani, guru yang pernah hadir di rapat LEKRA, atau warga desa yang sekadar ikut gotong royong di acara Gerwani. Mereka diburu, ditangkap, dibunuh, tanpa pengadilan. Pancasila yang katanya dijaga, justru saat itu seakan terkoyak: keadilan sosial diganti dengan pembantaian massal.
Di titik ini, sisi negatif PKI dan tragedi yang menyertainya tidak bisa ditutup-tutupi. PKI dengan retorika kerasnya turut memicu konflik, sementara peristiwa G30S menjadi noda yang selamanya melekat pada nama partai itu. Tetapi di sisi lain, negara pun tidak bersih dari darah: pembantaian massal yang terjadi setelahnya adalah kejahatan kemanusiaan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan.
Maka, ketika kita berbicara tentang PKI, janganlah hanya melihat satu sisi. Ia bukan hanya monster seperti dalam propaganda film lama, tetapi juga bukan malaikat yang bersih dari salah. PKI adalah bagian dari sejarah Indonesia yang penuh paradoks: di satu sisi membangkitkan kesadaran rakyat kecil, di sisi lain terlibat dalam konflik berdarah yang menodai bangsa.
Sebagai akademisi muda, saya belajar bahwa membaca PKI harus dengan kacamata kritis dan jernih. Jangan sekadar menelan propaganda, entah itu propaganda Orde Baru yang mendiskreditkan, atau romantisasi berlebihan yang menutup mata dari kesalahan. Sejarah menuntut keseimbangan: berani mengakui capaian positif, tetapi juga jujur pada luka yang ditinggalkan.
Tragedi 1965 menunjukkan betapa rapuhnya bangsa ini ketika ideologi dijadikan senjata. PKI jatuh karena tidak mampu menahan arus besar konflik global dan domestik. Namun bangsa Indonesia pun jatuh, karena membiarkan kebencian dan dendam menguasai nurani, hingga manusia dianggap tak lebih dari cap ideologi yang bisa dilenyapkan begitu saja.
Kini, puluhan tahun kemudian, yang tersisa adalah pertanyaan: apakah kita sudah berdamai dengan sejarah? Rasanya belum. Kita masih terjebak dalam narasi tunggal, masih enggan membuka arsip, masih takut menyebut nama PKI tanpa stigma. Padahal berdamai bukan berarti membenarkan, melainkan berani mengingat seluruh wajah sejara, baik yang gelap maupun yang bercahaya.
PKI akan selalu dikenang dengan dua wajah: wajah rakyat yang menemukan ruang perjuangan, dan wajah darah yang mewarnai tragedi G30S/PKI. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sejarah bukan hitam-putih, melainkan mozaik penuh warna, di mana terang dan gelap bercampur. Tugas kita adalah menatap mozaik itu dengan jujur, tanpa menutup satu sisi.
Karena pada akhirnya, sejarah bukan tentang menyalahkan semata, melainkan tentang belajar. Belajar bahwa kekuasaan tanpa nurani akan berujung pada luka, bahwa ideologi tanpa kemanusiaan hanya akan melahirkan darah. Dan yang terpenting: belajar bahwa rakyat kecil selalu menjadi korban, ketika para elite berperang atas nama ideologi.